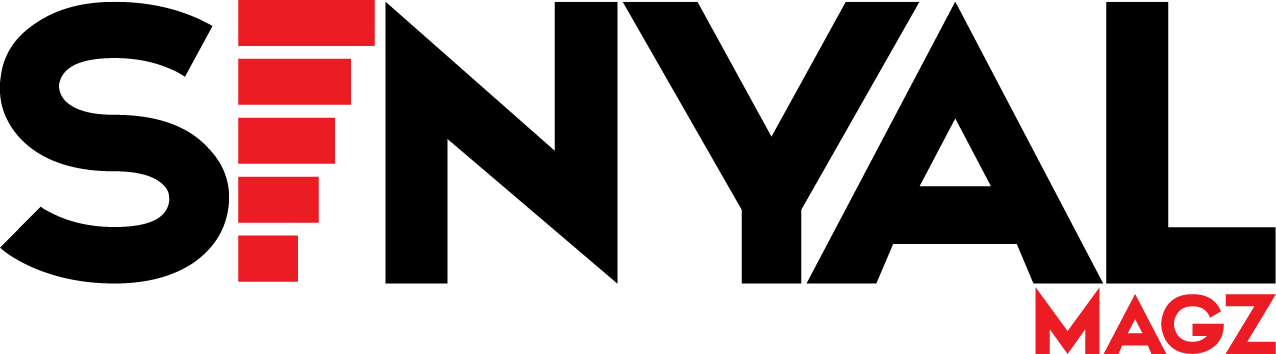sinyal.co.id
AWAL dekade 2000-an, da’i kondang Aa Gym (KH Gymnastiar) terkesan pada struktur bangunan Hotel Santika Jakarta ketika ia diundang berceramah pada silaturahim halal bil halal karyawan Kompas Gramedia. “Bangunan yang indah dan kokoh,” ujarnya waktu itu.
Namun bukan itu maksudnya. Bangunan bisa kokoh karena dibangun tidak hanya dari semen, atau hanya pasir, atau kayu, bahkan hanya oleh tukangnya. “Semua harus dipersatukan, baru menjadi bangunan yang kokoh”.
Segala sesuatu di dunia juga demikian, harus ada kerja sama antar bagian, antar komponen untuk bisa membuatnya punya arti. Sesuatu yang dibangun atau diciptakan sendiri oleh manusia pasti memiliki kekurangan. Secara alami manusia membutuhkan ciptaan Allah yang lain, benda mati, atau mahluk hidup untuk bercipta karya.
Ucapan Aa Gym ini tidak akan pernah basi, selalu punya konteks dalam setiap zaman. Selalu aktual, walaupun manusia sebagai mahluk dengan kemampuan jauh di atas mahluk lain acap berpikir egois, merasa tak perlu bantuan orang lain.
Di zaman modern Indonesia, kata-kata Aa Gym haruslah selalu didengungkan. Dalam masalah apa saja.
Juga dalam masalah upaya kita untuk memanfaatkan era digital bagi kemajuan bangsa. Dewasa ini orang sadar, tanpa digitalisasi, tanpa memanfaatkan pita lebar (broadband), kemajuan satu bangsa akan terhambat atau tersendat.
Masalahnya, pita lebar tidaklah dapat dikerjakan oleh satu orang sendiri, atau satu pihak saja tanpa keterlibatan orang lain. Industri pita lebar merupakan industri ilmu tinggi tetapi tetap perlu “keroyokan” karena perlu dukungan pihak lain yang berkaitan.
Pengembangan dan pemanfaatan digital dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam ekonomi berbagi, harus memenuhi unsur DNA (device – alat), network (jaringan) dan application (aplikasi). Device merupakan domain para manufaktur alat telko termasuk ponsel, network langsung dalam kendali operator sementara aplikasi dibuat oleh masyarakat atau operator dengan maksud melengkapi kemampuan alat dan jaringan agar dapat dijual. Aplikasi bisa berupa konten dalam berbagai bentuk.
Di lapangan, operator boleh meluncurkan layanan GSM generasi keempat (4G), namun bila ekosistemnya tidak mendukung, layanan 4G itu tidak bermanfaat. Misalnya tidak tersedianya ponsel atau device yang berteknologi 4G atau kalaupun ada baik dari sisi operator maupun sisi manufaktur device, tidak ada aplikasinya. Tidak ada kontennya sehingga tidak ada alasan bagi pelanggan untuk mengaksesnya.
Akhirnya pun tidak hanya DNA dan ekosistem yang berperan, sebab landasan hukum juga punya posisi menentukan, misalnya soal penggunaan frekuensi, pengaturan tarif, selain khusus bagi manufaktur adalah kejelasan industri.
Operator selalu berkata bahwa secara unit layanan 4G lebih murah dibanding generasi sebelumnya. Namun hal paling penting biaya sebenarnya tidak pernah disinggung padahal 4G akan mengenakan biaya yang jauh lebih mahal sesuai kemampuan pengiriman data yang besar.
Maka kemampuan unduh dan unggah yang besar, sampai di atas 100 Mbps, akan menjadi jebakan batman bagi pelanggan karena bisa saja tiba-tiba kuotanya habis tersedot dalam waktu singkat. Pada intinya, akses ke layanan 4G tidaklah cocok untuk pelanggan yang pas-pasan.
Survei menyebutkan, penghasilan per kapita penduduk Indonesia sudah Rp3,8 juta per bulan, dan ini diyakini mengangkat kemampuan pelanggan untuk mengakses layanan 4G, apalagi di pasar sudah banyak ponsel 4G berharga sekitaran Rp1 juta. Pemilikan ponsel pintar di kalangan masyarakat pun sudah tinggi tetapi sebagian memilikinya hanya karena ikut tren dan hampir tak pernah mengakses layanan 4G.
Dari jumlah penduduk 259 juta lebih, nomor yang beredar mencapai 326 juta (126 persen ), padahal jumlah nama pelanggannya (unique number) hanya 162,3 juta (63 persen penduduk) karena seorang pelanggan bisa punya lebih dari satu ponsel. Angka ini membuat ARPU (Average Revenue Per User – pendapatan operator dari rata-rata penduduk) rendah, hanya sekitar Rp25.000.
Kalangan manufaktur ponsel 4G yang sudah buka pabrik di Indonesia resah menyangkut soal TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri – Local Content) untuk produksi ponsel pintar yang hingga kini masih belum juga jelas, meski sudah dipatok TKDN 20 persen tahun ini dan 30 persen akhir tahun 2017. Kementerian Perindustrian memberi pilihan TKDN, bisa 100 persen perangkat lunak dan 0 persen perangkat keras atau sebaliknya, sampai masing-masing sama besar, 50-50.
Bagi merek yang sudah membangun pabrik ponsel 4G dan TKDN sudah 20 persen dengan polanya 50-50, aturan 100 persen perangkat lunak yang bisa berbentuk aplikasi akan merugikan mereka dan menguntungkan merek yang tidak mau membangun pabrik. Bisa saja merek yang menolak TKDN ini mengisi perangkat lunak berupa aplikasi lokal Indonesia di pabrik mereka di luar negeri, sehingga masuk pabean sudah memenuhi syarat TKDN.
Namun di lapangan, pabrik ponsel pun belum tentu mau menancapkan aplikasi lokal di ponsel 4G buatan mereka dengan berbagai pertimbangan, seperti yang dikeluhkan oleh beberapa pengembang aplikasi lokal. Hal sama juga dikeluhkan pengembang jika ingin konten mereka digunakan oleh operator, dan ini lebih parah karena ada saja operator yang menganggap pengembang aplikasi hanya menumpang cari makan ke operator dan tidak disetarakan sebagai mitra operator.
Hal-hal berbentuk arogansi sektoral dirasa akan masih menghambat pertumbuhan layanan digital di Tanah Air. Saling berbagi kesempatan, saling melihat apa yang dimaui pasar, barangkali bisa jadi jalan tengah untuk lebih memajukan penggunaan pita lebar dalam ekonomi berbagi.
Moch S. Hendrowijono